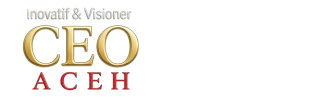Jejak yang Tak Terserahkan: Saat Arsip Pemilu Menguji Integritas Negara
Oleh Muhamad Ihwan – Pemerhati Kearsipan
Geger sengketa ijazah Presiden Joko Widodo kembali membuka ruang diskusi dalam tata kelola kearsipan nasional. Bukan hanya tentang selembar ijazah, tetapi tentang keutuhan ingatan negara. Di tengah silang sengketa di Komisi Informasi, publik menatap dua lembaga: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pertanyaannya sederhana namun menohok: di mana seharusnya jejak autentik administrasi pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu berada?
Menurut Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU, dokumen administrasi pendaftaran calon presiden dan wakil presiden periode 2014–2019 termasuk kategori arsip permanen. Artinya, masa simpannya telah habis di KPU dan seharusnya diserahkan ke ANRI sebagai arsip statis. Bila arsip itu tidak lengkap, tercecer, atau tidak diserahkan, yang dipertaruhkan bukan sekadar dokumen pendidikan seorang presiden, melainkan marwah kearsipan nasional pilar legitimasi administrasi publik yang menjamin kontinuitas sejarah bangsa.
Dalam sengketa informasi ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ANRI sudah menjalankan kewajiban sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ANRI menjawab secara resmi bahwa informasi arsip yang diminta tidak dikuasai atau dimiliki, karena belum diserahkan oleh pencipta arsip, yaitu KPU. Secara hukum administrasi, ANRI telah memenuhi kewajiban badan publik menjelaskan ketersediaan atau ketiadaan informasi. Namun di balik jawaban formal itu, muncul fakta getir: mata rantai penyerahan arsip nasional ternyata belum bekerja sebagaimana mestinya.
Padahal, sejak lama ANRI telah melakukan akuisisi terhadap arsip-arsip KPU yang bernilai kesejarahan dan permanen. Sayangnya, arsip yang kini menjadi objek sengketa yakni berkas administrasi pendaftaran calon presiden 2014–2019 tidak termasuk dalam kelompok arsip yang pernah diserahkan. Artinya, tanggung jawab hukum dan administratif atas arsip tersebut masih berada di KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (c) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang bermakna bahwa pencipta arsip bertanggung jawab terhadap arsip yang diciptakan sampai dengan diserahkannya kepada lembaga kearsipan.
Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang dapat menjerat ANRI secara pidana dalam perkara ini. Justru yang patut dievaluasi adalah kepatuhan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewajiban penyerahan arsip statis sesuai JRA yang telah ditetapkan sendiri oleh Kepala ANRI. Kewenangan ANRI bersifat strategis karena hanya Kepala ANRI yang berhak menetapkan JRA lembaga pusat dan daerah, maka ANRI pula yang berhak memantau, mengingatkan, bahkan memaksa lembaga pencipta arsip untuk menyerahkan dokumen permanennya.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga negara, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Arsip permanen bukan milik institusi pencipta, melainkan milik negara. Bila arsip itu tertahan di meja birokrasi, maka negara sedang kehilangan ingatannya sendiri. Di sinilah ANRI perlu memperkuat fungsi pengawasan kearsipan nasional tidak hanya menunggu penyerahan arsip, tetapi proaktif menelusuri arsip-arsip bernilai tinggi yang terancam hilang di tangan pencipta.
Kita memiliki contoh baik. Dokumen Perjanjian Damai Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) salah satu arsip paling monumental dalam sejarah perdamaian bangsa diserahkan langsung kepada ANRI oleh Menteri Kehakiman dan HAM saat itu, Hamid Awaludin, melalui Kementerian Sekretariat Negara. ANRI menyimpannya sebagai arsip negara, bukan sekadar catatan diplomatik, melainkan bukti hidup rekonsiliasi nasional. Contoh seperti ini seharusnya menjadi teladan bagi lembaga lain: bahwa arsip adalah simbol tanggung jawab sejarah, bukan hanya tumpukan kertas administrasi.
Kesadaran itu pula yang coba ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Pemerintahan Kabinet Kerja 2014–2019. Surat ini menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga untuk menyerahkan arsip kegiatan pemerintahan yang bernilai sejarah ke ANRI. Ketentuan serupa bahkan diteruskan untuk periode Kabinet Indonesia Maju 2019–2024. Artinya, pemerintah sudah memiliki mekanisme formal agar memori pemerintahan tidak hilang. Tinggal komitmen dan ketegasan pengawasan yang menjadi taruhan.
Dari sisi hukum, ANRI telah berada di posisi yang benar. Delik aduan terhadap lembaga ini tampak mengandung salah alamat. Sebab, sistem kearsipan negara bekerja berdasarkan prinsip chain of custody: arsip baru menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan setelah proses serah terima dilakukan sesuai berita acara. Selama itu belum terjadi, tanggung jawab penuh berada pada pencipta arsip. Maka, jika ada kekosongan arsip, kesalahan administratif tidak dapat langsung dibebankan pada ANRI.
Namun persoalan ini jangan berhenti di ruang pembelaan hukum. Ini seharusnya menjadi momentum pembenahan sistem kearsipan nasional secara total. ANRI perlu memperkuat fungsi pembinaan, melakukan audit kearsipan lintas lembaga, dan mengintegrasikan basis data arsip statis secara digital agar publik dapat mengetahui dengan pasti di mana sebuah arsip negara berada.
Lebih jauh, kasus ini juga menggambarkan rapuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya arsip dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam konteks pemilu, arsip bukan hanya dokumentasi administratif, tetapi bukti sah atas proses konstitusional yang melahirkan pemimpin negara. Bila arsip pemilu tidak tertib, maka seluruh sistem legitimasi politik ikut tergerus.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki fase baru yang penuh tantangan. Dalam satu tahun pemerintahannya, Prabowo telah menorehkan catatan penting di dalam dan luar negeri dari diplomasi pertahanan hingga gagasan ketahanan pangan nasional. Di tengah gebrakan itu, ANRI harus berdiri di garis depan sebagai penjaga memori pemerintahan. Lembaga ini perlu memastikan setiap kebijakan, perjanjian, kunjungan, dan keputusan kenegaraan terdokumentasi secara autentik dan aman.
Lebih dari sekadar kewajiban administratif, penyelamatan arsip pemerintahan Presiden Prabowo adalah upaya menjaga mozaik sejarah bangsa. ANRI dapat secara proaktif mencatat, merekam, dan mengakuisisi arsip strategis pemerintahan agar tidak tercecer dalam dinamika politik dan birokrasi. Setiap pidato, kebijakan, dan dokumen internasional yang dihasilkan pemerintah hari ini adalah memori kolektif bangsa esok hari.
Arsip bukan sekadar jejak masa lalu, melainkan kompas moral bagi masa depan. Bila negara abai terhadap arsipnya, ia sedang mengikis kepercayaan rakyat terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, bila negara menjadikan arsip sebagai dasar transparansi dan akuntabilitas, maka bangsa ini akan berdiri tegak di atas kebenaran sejarahnya sendiri.

Polres Bener Meriah Gelar Peringatan Maulid 1444 Hijriah Kapolda Aceh Salurkan Puluhan Paket Bansos untuk Korban Banjir di Aceh Timur Disbudpar Aceh Melalui UPTD Taman seni dan budaya Aceh akan menggelar pagelaran Seni dan Budaya Bareskrim Sudah Periksa 22 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Jet Pribadi Hendra Kurniawan Kapolda Aceh Salurkan Bansos untuk Korban Banjir di Aceh Utara